Novel Handoko Adinugroho
Mimpi menjadi perwujudan bawah sadar komunikasi itu. “Saya ada tabungan dari mengumpulkan sedikit demi sedikit pemberian paman. Uang itu saya kira cukup untuk biaya saya pulang, Paman,” ucapku setelah agak mampu menguasai diri. Kulihat paman menggeleng. “Kenapa, Paman?” “Sebaiknya kau tak usah pulang. Doakanlah ayahmu dari sini.” “Tapi saya ingin melihat jenazah beliau. Saya ingin mencium jasad beliau untuk terakhir kalinya.” “Paman tahu. Paman sangat bisa memahami keinginan dan perasaanmu. Tapi seyogyanya tak kaulakukan itu. Lakukanlah apa saja yang menurutmu terbaik, tetapi cukup dari sini. Tak perlu ke sana.” Aku merasa paman menegaskan hal itu. Sangat memberi penegasan. “Mengapa, Paman?” Kulihat paman kembali merenung. Ia seperti merancang kalimat yang tepat untuk disampaikan. Aku semakin merasa penasaran. “Ayahmu wafat setelah diambil,” kata paman akhirnya. “Diambil bagaimana, Paman? Apa maksudnya?” “Ayahmu dibawa ke pos. Seminggu kemudian beliau ditemukan sudah wafat terapung di sungai.” “Astaghfirullahaladzim...” Aku kehabisan kata-kata. Lidahku seketika kelu. Mataku terasa nanar sebelum akhirnya tak kurasakan apa-apa lagi. Kunang-kunang beterbangan di kepalaku. Makin lama terasa semakin pekat hingga akhirnya gelap. Sangat gelap. Dan sunyi.
Aku kembali melihat sinar ketika kurasakan sudah berada di tempat tidur. Kubuka mata dan kulihat paman duduk di kursi di dekat jendela kamarku. Paman mendekat ketika melihat kelopak mataku bergerak-gerak. Kulirik jam di dinding, sudah menunjukkan pukul 09:00. Ketika kucoba bangkit, paman melarang. Beliau memintaku lebih baik merebahkan diri dulu. Pelan-pelan kucoba mengingat apa yang baru saja kualami. Tentang paman dan Gamal yang tak berolahraga pagi seperti biasa. Tentang keduanya yang berbincang sangat serius di meja makan. Tentang aku yang kemudian diminta ikut duduk di situ. Tentang kabar dari Indonesia. Tentang ayah yang telah wafat. Tentang ayah diambil. Tentang sungai. Tentang pos. Ya, pos.
Ingatanku lantas kembali ke masa lalu, ketika kulihat Nyak Umar dibawa ke sebuah truk bersama banyak orang lain. Saat itu orang-orang bilang, Nyak Umar dibawa ke pos. Aku tetap tak tahu pos semacam apa yang dimaksudkan. Apakah kantor pos? Jika memang kantor pos, mengapa Nyak Umar kembali dengan tubuh yang tak lagi memiliki daya?
Aku yakin, ayah pasti juga dibawa ke pos yang sama dengan pos tempat dulu Nyak Umar berada. Aku yakin, Nyak Umar mendapat perlakuan yang sangat hebat hingga menyebabkan kedua kakinya lumpuh. Aku juga lebih yakin lagi, ayah pasti mendapat perlakuan yang jauh lebih hebat dari Nyak Umar. Buktinya, Nyak Umar hanya lumpuh dan terbaring di balai-balai di teras rumahnya, sedangkan ayah harus ditemukan di sungai dalam kondisi yang sudah tak lagi bernyawa. Tak bisa kubayangkan seperti apa kondisi jasad ayah saat itu. Aku bahkan tak berani membayangkan, apakah jasad ayah masih utuh ataukah sebagian sudah rusak lantaran dijarah binatang-binatang air. Aku tak sanggup membayangkannya. Aku tak sanggup menanggungkannya. Yang tak habis kumengerti, mengapa ayah diambil? Mengapa ayah dibawa ke pos?
“Ayahmu dituduh melindungi GPK,” jawab paman ketika kutanyakan soal itu.
Lagi, kata itu kudengar setelah sekitar tiga tahun tak pernah mampir di telingaku. GPK. Kata – atau lebih tepatnya barangkali singkatan – yang selalu dikemukakan oleh sebarisan orang berpakaian loreng yang setiap hari hilir mudik mengelilingi kampungku. Orang-orang yang tak berwajah bengis, namun tidak juga bisa diartikan berwajah manis.



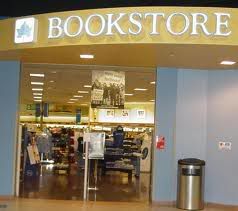





Belum ada komentar untuk "Aku Bukan Teroris - 10"
Tambahkan komentar anda :
Silakan tulis Komentar anda ...